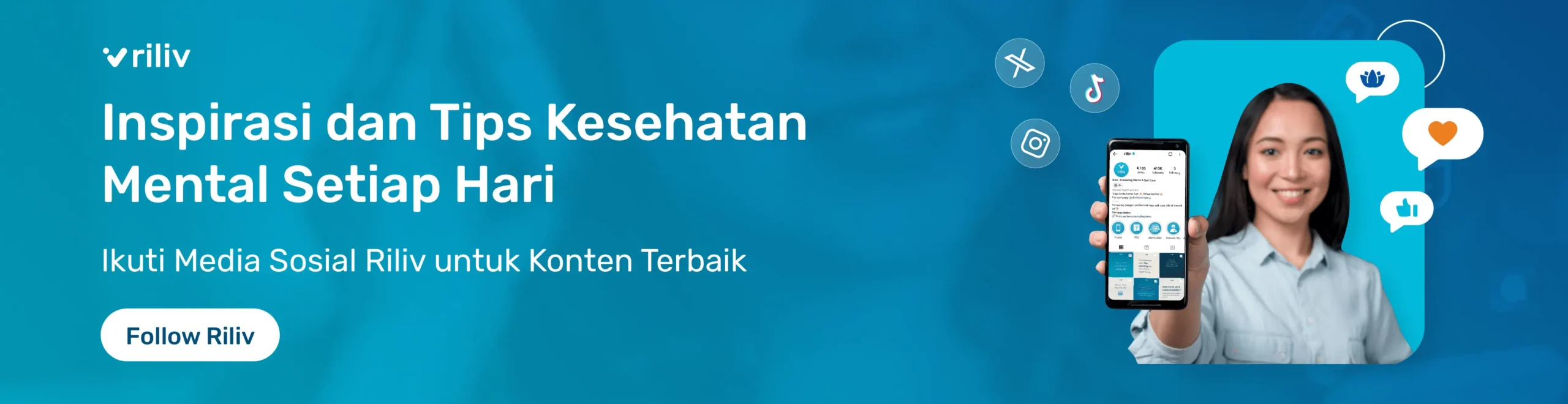Dear, pasti kamu sudah tidak asing lagi dengan film pendek berjudul Tilik. Baik sudah menonton atau belum, tiba-tiba saja, film pendek berbahasa Jawa ini menjadi buah bibir di sirkel, lapisan sosial, dan lapisan usia berapapun.
Tiba-tiba saja, film pendek dengan twist yang tidak biasa ini menjadi kegemaran, maupun mendapat kritik dari banyak orang, baik dari segi sosial, moral, dan etika.
[Artikel ini mengandung spoiler]
Tilik mengisahkan tentang sekumpulan ibu-ibu dari sebuah desa yang berangkat bersama dengan pick-up untuk menjenguk (dalam bahasa Jawa: tilik) Bu Lurah yang sudah sakit keras di rumah sakit kota.
Sepanjang perjalanan, obrolan mereka bergerak seputar Dian, wanita muda yang belum diberitahu rupanya dari awal hingga mendekati akhir film.
Bu Tejo, perempuan dengan baju matching biru emerald sekujur tubuhnya, membuka pembicaraan mengenai Dian dengan nada-nada yang pedas dan cenderung menuding.
Perlawanan Yu Ning terhadap angin-angin sinis yang dibawa oleh Bu Tejo sudah ada sejak pertama kamera menyorot wanita berkerudung coklat ini.
Setiap argumen dengan dasar etika dan tata krama dalam berasumsi yang dilemparkan Yu Ning, akan ditentang Bu Tejo dengan logika yang ia rasa lebih ‘realistis’. Bahkan, Bu Tejo sempat menyinggung status Yu Ning sebagai saudara jauh Dian.
Perdebatan mereka berlanjut hingga hampir tiba di tujuan. Keadaan semakin memanas, terutama Yu Ning tetap berpegang pada pendiriannya bahwa tidak baik bersikap asumtif akan sesuatu yang belum sepenuhnya kita ketahui.
Sementara Bu Tejo, dengan semangatnya menonjolkan kedahsyatan infomasi media sosial dan sikap yang selalu berjaga-jaga, terus bersikeras dengan pendiriannya, dengan alasan ‘menjaga keutuhan rumah tangga warga desa dari perempuan yang tidak baik’.
Di akhir cerita, bertemunya para ibu-ibu dengan Dian dan Fikri (anak Bu Lurah) seakan memvalidasikan satu dari sekian asumsi Bu Tejo, bahwa Dian memiliki kedekatan dengan Fikri.
Kedekatan singkat di depan mata mereka semua itu, membuat Bu Tejo semakin yakin bahwa sikap yang selama ini ia jadikan prinsip, adalah sikap yang tepat. Namun, mengapa penonton Tilik masih membenci dan gemas dengan figur Bu Tejo?
Mengesampingkan kenyataan bahwa asumsi Bu Tejo mendekati ‘benar’, kali ini Riliv akan mengajak Anda untuk ‘menilik’ sisi lain dari Bu Tejo versus Yu Ning dari sudut pandang mindfulness.
Menilik dahulu mengenai apa itu mindful speaking
 Photo by August de Richelieu from Pexels
Photo by August de Richelieu from Pexels
Mindfulness disebut sebagai kemampuan mendasar kita sebagai individu untuk sadar dan awas akan kejadian di sekitar kita, dan segala bentuk respons yang kita keluarkan.
Dalam arti, dibanding berlaku impulsif atau ‘autopilot’, seseorang dengan pikiran dan perbuatan yang mindful akan sadar akan perbuatannya, dan awas akan hasil dan resiko dari pikiran, perkataan, dan perbuatan yang akan ia keluarkan.
Mindfulness dianggap sebagai kemampuan yang sebenarnya sudah ada di dalam diri semua orang, dan hanya membutuhkan keinginan kita untuk belajar dan ‘mengakses’ kemampuan itu dalam diri kita, dan menghidupi kemampuan ini dalam keseharian kita.
Setiap manusia tidak akan luput dari kesalahan. Dengan belajar mindfulness, bukan berarti seseorang bisa terhindar dari salah bicara atau salah bertindak.
Namun, jika kamu sudah memilih untuk hidup mindful, refleksmu terhadap tindakan-tindakan impulsif akan lebih cepat. Bahkan, kamu pun bisa memanfaatkan pikiran yang mindful dalam mencari solusi atas kesalahan yang terlanjur dibuat.
Benar vs Tepat: mengapa Bu Tejo masih dibenci meski terbukti (hampir) benar?
Akhir cerita dari Tilik hampir tidak terduga bagi siapa saja. Dari tiga asumsi Bu Tejo mengenai keadaan Dian: profesi wanita malam, simpanan pria lanjut usia, dan berhubungan dengan Fikri, asumsi kedua adalah asumsi terdekat dari akhir cerita.
Meski, siapapun di truk itu bahkan tidak menduga bahwa pria lanjut usia tersebut adalah suami dari lurah desa mereka.
Alasan yang cukup populer dan sederhana tercetus dari banyak respons netizen. Terutama pergolakan batin beberapa penonton tentang ‘menangnya peran penjahat’ dalam sebuah cerita.
Ending Tilik juga dikhawatirkan akan mendukung cyberbullying, gosip, dan kecenderungan fitnah.
Hal-hal yang netizen takuti tersebut adalah hasil-hasil akhir dari sikap yang tidak mindful. Dan disinilah peran mindful speaking bisa digunakan.
Kita bisa mengasumsikan bahwa tindakan Bu Tejo muncul dari tindakan autopilot; di mana seseorang merespons situasi dan informasi yang ia dapat secara impulsif. Terutama bila Bu Tejo bersikeras bahwa kewaspadaan ibu-ibu terhadap figur Dian yang dianggap ‘nakal’ bisa mengancam rumah tangga mereka.
Sangat penting bagi kita untuk mengambil jeda sebelum berbicara dan membiarkan napas keluar dan masuk ke dalam paru-paru kita, sehingga kita bisa rileks dan mengeluarkan keputusan-keputusan yang jernih.
Dengan perkataan yang lebih mindful, tentu kita bisa mengurangi ketersinggungan yang bisa kita bawa, dan menghargai lawan bicara kita.
Maka, dengan pembawaan yang lebih mindful, mungkin saja perdebatan Bu Tejo dan Yu Ning tidak akan terjadi, dan mungkin saja tidak akan terjadi slek yang Yu Ning rasakan.
Motivasi dalam menyampaikan perkataan sangatlah penting. Tanpa motivasi yang kuat, pembicaraan kita akan bergerak secara tidak jelas dan tidak bersadar. Hal ini tentu akan mengarah kepada komunikasi yang buruk dengan lawan bicara kita.
Motivasi yang salah pun wajib ditelusuri dan dipikirkan kembali resikonya. Dengan itu, jika tujuan Bu Tejo benar untuk berjaga-jaga dan melindungi kelanggengan rumah tangga ibu-ibu di desanya, maka tujuan itu bisa terlaksana dengan lebih baik dan kooperatif, dengan komunikasi yang tidak ofensif/menyerang.
“Apakah mindfulness sepenting itu untuk dipelajari oleh seluruh lapisan masyarakat?”
Tidak sedikit yang memaklumi kejadian dalam film pendek Tilik, dengan mewajarkan pola pikir dan perilaku dari potret masyarakat kelas menengah ke bawah yang ada pada film ini.
Netizen merasa bahwa hal ini sangat wajar terjadi pada orang-orang yang kurang berpendidikan, atau yang masih harus fokus pada masalah mendasar, seperti keuangan dan keluarga kecil.
Berdasarkan logika ini, tentu mindfulness dianggap sebagai ilmu yang ‘mahal’ bagi masyarakat desa.
Namun, tentu saja tidak baik bila kita membatasi hal-hal yang baik bagi kesehatan mental sebagai ‘makanan’ bagi warga kota atau orang kaya saja. Mengasumsikan bahwa mindfulness bertindak sebagai ilmu yang harus dipelajari lewat seminar-seminar dan buku-buku mahal juga kurang baik.
Mindfulness bisa menjelma dalam bahasa-bahasa yang lebih sederhana: legowo, berempati, memikirkan sesama, dan menjaga hati saudara.
Persaudaraan dan kelekatan dari komunitas masyarakat dalam lingkup kecil sangatlah kuat. Terutama, bagi warga di desa Bu Tejo.
Mindfulness yang menjelma menjadi bahasa yang sederhana sangat mudah untuk diedukasikan dan diimplementasikan bagi lapisan masyarakat apapun, terutama bila kita memegang kuat pola pikir “perlakukanlah saudaramu seperti kamu ingin diperlakukan“.
Peran mindful thinking bisa diaplikasikan di sini: apakah kamu akan suka bila seseorang berbuat seperti ini kepadamu? Apakah kamu ingin ada yang tetap menolong tanpa asumsi dan praduga ketika kamu sedang berada dalam masa sulit?
Mungkin, dengan mindful speaking dan mindful thinking, film pendek Tilik tidak akan terjadi dan tidak akan menjadi sebuah film pendek yang seru dan membuat kita geregetan. Namun, Bu Tejo adalah cautionary tale atau kisah jaga-jaga yang bisa kita jadikan bahan refleksi yang dapat mendorong kita untuk lebih mempelajari tentang mindfulness.
Sumber:
- https://www.mindful.org/what-is-mindfulness/
- https://www.futurelearn.com/courses/mindfulness-life/0/steps/34474
Ditulis oleh: Rachel Emmanuella