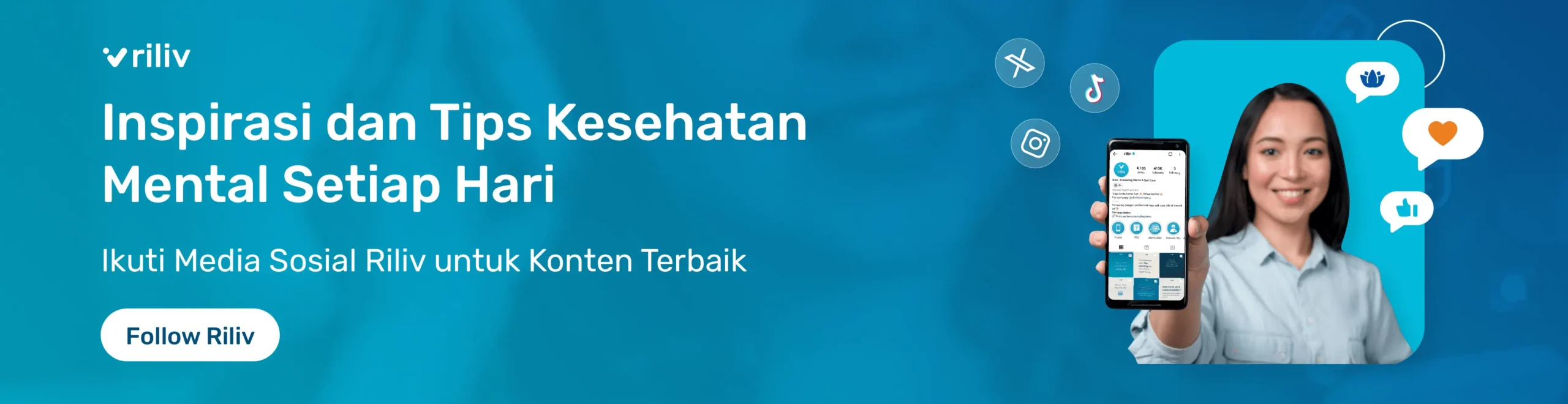Depresi Anak Sulung Perempuan – Selalu ada suka dukanya menjadi anak sulung, apalagi jika kamu anak sulung perempuan, seperti yang akan diutarakan teman kita dalam cerita ini.
Hai Riliv!
Setelah 24 tahun aku menelan semuanya sendirian, rasanya ini adalah waktu yang tepat untuk aku berusaha menyembuhkan diriku secara perlahan. Apalagi, Riliv sudah membantuku untuk meredakan beberapa hal yang selama ini aku takutkan, salah satunya melalui metode journaling di aplikasi Riliv.
Aku percaya setiap orang punya cobaan hidupnya masing-masing, namun bagiku, cobaan hidupku ini begitu pahit. Kadang aku merasa iri karena orang di luar sana memiliki keluarga yang utuh, penuh cinta dan kasih, serta saling melengkapi. Keluarga seperti itu adalah dambaanku setiap saat. Rasa iri itu sering bergejolak ketika aku bertemu teman-temanku yang ditemani oleh kedua orang tuanya lengkap dan terlihat begitu hangat. Aku bukan tidak memiliki keluarga, bukan. Hanya saja aku tidak memiliki keluarga yang penuh kasih sayang seperti teman-temanku.
Secara legal, status pernikahan kedua orang tuaku masih bersama. Namun secara emosional, keduanya sangat tidak akur. Sejak kecil, aku dan adik perempuanku sudah cukup sering mengalami hal-hal yang tidak seharusnya kami rasakan dalam sebuah keluarga.
Kekerasan fisik dan verbal seringkali kami alami, terutama terhadap ibu. Belum lagi kasus perselingkuhan, hidup serba kekurangan, dan ekonomi yang tak terpenuhi membuat kami hampir putus sekolah. Kami bisa tuntas sekolah hampir 80% dengan beasiswa. Dan yang berusaha keukeuh untuk menyelesaikan pendidikan kami adalah Ibu. Kata Ibu, kami harus tuntas sekolah sampai perguruan tinggi, karena harapan Ibu hanya terletak pada kami.
Sesusah apapun perjalanannya, Ibu akan selalu berusaha memenuhi asal pendidikan kami tetap berjalan lancar. Awalnya, Ibu hanya seorang ibu rumah tangga, namun karena keadaan keluarga yang kian memburuk semakin tahun Ibu berusaha memenuhi ekonomi keluarga dengan banyak cara. Antara lain dengan berjualan kue, menjahit, menjadi ART harian, dan lainnya. Asalkan pekerjaannya tidak melanggar agama dan norma, tidak masalah untuk dilakukan, bukan? Begitulah perjuangan Ibuku, yang rela bersusah payah agar anak-anaknya tetap bisa makan dan bersekolah.
Mungkin kalian sudah tahu siapa yang menyebabkan hidup kami begitu banyak drama. Ya, pelaku utamanya adalah ayah kami. Kata orang, ayah adalah cinta pertamanya anak perempuan. Namun sayangnya, hal itu tidak berlaku padaku dan adikku. Akibat perlakuan tersebut, aku merasa tidak memiliki keluarga utuh sejak kecil.
Dulu, aku tidak pernah tahu apa yang aku rasakan, namun setelah aku berkuliah di psikologi, aku menyadari bahwa rentetan peristiwa ini membuatku mengalami gejala depresi. Depresi yang diakibatkan permasalahan yang kualami. Keluargaku hanya secara legal di Kartu Keluarga saja, namun selebihnya, ini bukanlah keluarga yang ideal bagiku.
Sebagai anak sulung perempuan yang mengalami gejala depresi, aku mulai merasa beban hidupku semakin bertambah, dimana aku wajib menjadi back up ibu dan adikku sampai kapanpun. Kami telah menjalani kehidupan yang sangat buruk. Akibat kejadian itu, aku tumbuh menjadi pribadi yang selalu siap bertahan di segala medan. Di sisi lain, aku dipaksa untuk mandiri, dan aku merasa tidak perlu bantuan orang lain. Aku juga merasa tidak percaya dengan komitmen jangka panjang. Aku ingin menjalani hidup sehari-harinya hanya untuk satu tujuan, ibu dan adikku.
Namun saking fokusnya dengan tujuan hidupku, aku lupa bahwa aku adalah manusia. Aku juga memiliki rasa sedih. Aku telah terbiasa mengesampingkan perasaanku, selalu meletakkan rasa sedih untuk menutupnya dengan kesibukanku. Memang, itu membuatku lupa dengan rasa sedihku. Namun di psikologi, kita diajari untuk mengenali emosi dan menerimanya. Emosi yang kita miliki harus benar-benar kita rasakan, karena emosi yang ditahan bisa meledak di kemudian hari.
Dan ya, aku pernah merasakan dampaknya karena tak mampu mengontrol emosi. Sewaktu-waktu, aku bisa menangis hebat sampai gemetar, dan seringkali berteriak, pernah beberapa kali menyakiti diri sendiri dengan menjambak rambutku. Kepalaku begitu sakit karena emosi yang meledak-ledak itu.
Mungkin itulah akibatnya terbiasa tidak memikirkan diriku sendiri. Seperti yang aku katakan sebelumnya, tujuanku hidup hanya untuk ibu dan adikku. Aku pernah beberapa kali memikirkan tentang kematian, tapi aku masih percaya bahwa Tuhan menciptakanku untuk sebuah tujuan yang baik. Aku pernah punya mimpi dan terpaksa harus aku urungkan demi ibu dan adikku. Beberapa mimpiku gugur karena sebuah keadaan.
Tinggal ada dua mimpi yang tersisa. Aku akan berusaha keras untuk mewujudkan hal itu. Pertama, aku ingin menjadi seorang psikolog. Syukurlah, karena kali ini aku sudah menempuh semester 3, meski harus bersusah payah karena disambi bekerja. Kedua, aku ingin menciptakan sebuah keluarga yang aku dambakan sejak dulu. Meskipun rasa trauma terhadap sebuah pernikahan sangatlah besar, aku sedang berusaha menyembuhkannya secara perlahan.
Inilah kedua mimpi yang paling ingin aku wujudkan.
Aku adalah manusia. Aku juga berhak bahagia, bukan? Karenanya, aku akan menempuh banyak cara untuk bisa mewujudkan 2 mimpiku itu.
Kembali lagi pada keluargaku. Aku tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayahku. Keluargaku tengah mengalami perang dingin, begitulah kata orang-orang. Namun berkat pengalamanku, aku sudah lebih berani berdebat dengan ayahku sekarang. Aku ingin mengambil semua keputusan tentang hidupku, ibu dan adikku. Terkesan kurang ajar memang, tapi di tengah keterpurukan keluarga ini, aku perlu untuk bersuara. Aku lelah jika harus terus menerus mengikuti permainan Ayah.
Ayahku lupa bahwa aku anak pertama, yang harus siap menjadi back up keluarga. Ayahku lupa bahwa aku anak pertama, yang harus tangguh dalam segala medan. Ayahku lupa bahwa aku anak perempuan, yang hatinya perlu diberi sentuhan lembut dari seorang ayah. Selain itu, aku juga akan menjadi seorang istri. Bagaimana aku bisa kuat menghadapi semuanya bila ada bayang-bayang cerita tidak mengenakkan dari keluargaku? Pernahkah terpikirkan olehnya? Berkaca dari perlakuannya terhadap aku, ibuku, dan adikku, rasanya tidak.
Perjuanganku ini bukan hanya tentang aku sendiri untuk bahagia. Ibu dan Adikku juga berhak untuk bahagia. Syukurlah, Ibu telah memutuskan bahwa akan bercerai. Coba tebak apa yang aku rasakan saat mendengar keputusan itu?
Aku merasa hampa. Aku benar-benar sudah tidak bisa merasakan apa pun. Melihat ibu menangis saja aku hanya melihatnya dari sudut kursi, tidak bisa merasakan emosi yang sama dengan ibu. Aku telah terbiasa bertindak menggunakan logika, mengesampingkan perasaan.
Justru ketika Ibu memutuskan hal itu, aku langsung berpikir tentang bagaimana aku bisa bertanggung jawab atas hidup Ibu dan adikku setelah ini. Apalagi, kondisi keuanganku masih belum stabil. Aku juga masih ingin mengejar mimpiku untuk tetap bisa lulus magister profesi. Bila harus menambah kerja sampingan, aku sudah tidak memiliki waktu. Keadaan fisikku pun sudah tidak mampu.
Ya, Riliv. Aku belum bisa sembuh dari gejala-gejala depresiku. Sudah dua minggu lamanya aku tidak banyak berbicara dengan Ibu, padahal Ibu mengenalku dengan pribadi yang ceria, talkative, dan manja. Setiap Ibu mengajakku berbicara, aku lebih sering menghindar. Aku hanya tidak ingin banyak bicara untuk sekarang, aku tidak tau harus bagaimana. Aku selalu menjawab Ibu dengan alasan, “Aku butuh waktu.”
Namun, aku sadar bahwa sebenarnya aku tidak butuh waktu, tapi aku hanya mengulur waktu untuk tidak merasakan sedih yang mendalam. Akhirnya, kemarin aku menangis hebat sampai tertidur. Lega rasanya karena bisa merasakan emosi sendiri. Meskipun aku belum bisa sembuh dari masalahku, setidaknya aku bisa berpikir lebih rasional sekarang.
Riliv, aku tidak tau hidupku akan jadi seperti apa setelah perceraian orang tuaku. Padahal sebenarnya aku oke saja atas keputusan itu. Aku masih memikirkan bagaimana aku bisa menjadi satu-satunya tiang yang harus bisa berdiri kokoh untuk ibu dan adikku. Pertanyaanku masih sama: apakah sebagai anak sulung perempuan aku masih bisa mencapai kebahagiaan untuk diriku sendiri?
Yah, biarlah waktu yang menjawabnya. Intinya, aku sudah lelah menjadi tiang yang harus selalu kokoh. Kuharap aku bisa bertahan sekuat mungkin dengan segala keadaan yang kualami.
Salam hangat!
.
Sumber cerita: A, kontributor Riliv.
—
Kisah ini ditulis dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan pengalaman nyata dari para pejuang sehat mental terpilih, yang telah mengikuti rangkaian acara MindFest 2022, a mental health event by Riliv. Rangkaian acara ini membawa misi bahwa semua orang berhak untuk #SehatMental dan mendapatkan akses serta layanan kesehatan mental tanpa terkecuali.
Karena #UdahSaatnya, kesehatan mental jadi prioritasmu.